H A N A
HANA by. Lindsay Lov’
Bukan hanya aku, semua orang di desaku, bahkan mungkin semua orang di dunia terkejut dengan musibah yang menimpa negaraku. Tsunami yang begitu mendadak datangnya, begitu besar dan mengerikan telah memporak-porandakan semuanya. Rumah-rumah, gedung-gedung, jalan raya, dan yang terparah adalah meledaknya power plant - pembangkit listrik tenaga nukir – yang sesungguhnya berjarak jauh dari desa tempat tinggalku. Tak bisa kubayangkan, betapa banyak jerit tangis pilu di saat bayangan kematian datang dan menyapu bersih beberapa desa bagaikan air bah yang mengamuk marah. Tak bisa kubayangkan, ribuan mayat bergelimpangan diseluruh penjuru, yang kondisinya sudah tak terbentuk, bahkan terpisah dan hilang entah kemana. Tak juga bisa kubayangkan betapa dua tahun ini adalah masa-masa penuh kesedihan, penuh kenangan pahit, dan penuh air mata untuk bangkit dari situasi yang begitu berat, begitu sedih. Ya Tuhan, kenapa? Kenapa cobaan yang kau berikan kepada kami begitu berat? Apa kesalahan kami sehingga kau menegur kami dengan musibah yang begitu dahsyat?
"Haruka, cepat turun sarapan. Hari ini banyak yang mesti kita lakukan!" teriak ayah dari dapur.
Aku bangkit dengan enggan setelah menyimpan buku diaryku ke dalam lemari. Kulirik, jam masih menunjukkan pukul lima pagi. Masih pagi sekali, dan kami memang harus bangun. Udara dingin memaksaku memakai mantel tebal dan penutup kepala rajutan ibuku. Benar kata ayah, hari ini banyak yang mesti kami lakukan. Teramat banyak, namun teramat berat.
"Haruka, kenapa kau tidak menghabiskan sarapanmu?" tegur ayah lembut saat melihatku membawa piring makanku yang masih penuh ke tempat cuci piring.
"Aku...masih kenyang, Yah." jawabku berbohong. Tentu saj, mana mungkin aku bisa kenyang padahal ayahku tahu pasti, tadi malam pun aku sudah tidak bisa makan, setelah kabar dari pemerintah sampai ke desa kami.
"Haruka, ayah tidak mau melihatmu sakit. Kau tidak perlu memikirkan semua ini. Biar ayah yang memikirkannya," ujar ayah seraya merangkul bahuku. Aku langsung membalik dan memeluk ayahku dengan erat. Aku ingat dengan ibuku. Disaat-saat seperti ini, biasanya ibulah yang paling mengerti bagaimana cara untuk menghapus kesedihanku. Tetapi dimana ibu? Ibuku hilang. Ibuku tidak tahu berada dimana semenjak musibah tsunami dua tahun yang lalu itu terjadi. Seingatku, ibu pergi mengunjungi nenek yang sakit, dan sehari sesudah itu, tsunami menyapu rata desa nenek, dimana ibu berada saat itu. Ayah dan aku sudah berusaha mencari kesana kemari, bertanya pada pemerintah, menyebar foto kemana-mana, dan aku juga mencoba mencari lewat internet, keseluruh dunia. Namun ibu bagai hilang ditelan bumi. Jenazah nenek dan kakek ditemukan. Juga jenazah dua orang pamanku serta keluarga mereka. Tetapi tidak dengan ibuku. Kenapa, ya Tuhan? Kenapa hanya ibuku? Dimana Ibu? Masih hidupkah ia?
"Haruka, sudahlah. Kalau kau tidak sanggup, biar ayah saja..."
"Tidak, Yah. Aku ikut," ucapku seraya mengelap air mata yang menetes di pipiku. Ayah menatapku dengan iba, dan lalu menggenggam tanganku. Mencoba memberi kekuatan. Lalu kami melangkah menuju peternakan.
Aku sungguh tak percaya ketakutan kami kembali membayang. Pemerintah mengumumkan power plant yang dibangun cukup jauh dari desa kami, sekitar 25 km, meledak dan radiasinya sudah mulai mencapai desa kami. Dalam waktu sebulan, seluruh warga harus mengosongkan desa, agar tidak terkena paparan radiasi nuklir yang berbahaya bagi kesehatan. Saat ini, air sungai di ujung desa sudah terpapar radiasi. Begitu juga tanaman dan hutan di kaki gunung. Sesaat lagi semuanya akan mengering dan mati. Hewan- hewan kecil sudah berjatuhan, dan mati dengan mengenaskan.
"Pak Kiramoto..." terdengar suara Kenji diluar rumah, bediri menanti bersama dua orang pekerja lainnya. Mereka tampak berjuang melawan kesedihan, "Apa tidak ada jalan keluar lainnya..."
"Tidak." Tegas ayahku cepat. "Ayo segera kasih makan sapi-sapi itu agar tidak
kelaparan."
Kenji menatap sesaat. Matanya memerah. Lalu dia menoleh kearahku, seolah meminta bantuan. Tetapi aku malah membuang muka dan lari kepeternakan. Ayah tampak tegar dan tegas seolah tidak dapat dibantah. Namun aku tahu, diantara kami semua, ayahlah yang paling terluka. Setelah kehilangan istri, ia juga harus kehilangan rumah dan peternakan sapi yang sudah dibangun selama enam puluh tahun. Aku tahu ayah yang paling menderita diantara kami semua, saat aku mendengar pembicaraan ayah di telepon tadi malam.
"Aku tidak ingin uang kalian. Aku ingin hidupku kembali. Hanya itu!" teriak ayah saat pemerintah menegaskan agar kami segera pindah dan menjual semua hewan ternak yang masih sehat kepada pemerintah untuk segera disembelih.
"Hana..." ucapku terbata-bata disela isak tangisku. Aku membelai kepala sapi betina yang menggigit-gigit lengan bajuku. Hana adalah sapi kesayangan ibu. Ia selalu mengingatkan aku pada ibuku, karena saat kelahirannya, aku dan ibu yang membantu. Aku sangat mencintainya, dan Hana juga mencintaiku.
"HANAA..." kini suaraku berubah menjadi jeritan saat Hana dan seluruh sapi dari peternakan ayah digiring masuk ke dalam truk pemerintah. Ayah memelukku, meredam duka di dalam hati kami.
# sekilas fiksi dari tragedi tsunami, Jepang.
#DaySeven#OneDayOnePost
#BayarHutang
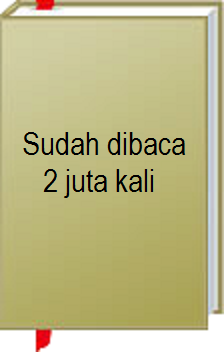

Comments
Namanya imut